#POROS KEMANUSIAAN
Hud-hud Musa kembali dari perjalanannya di dunia digital. Sayapnya lelah oleh cahaya layar. Ia datang ke Balé Beléq, tempat ia biasa menemui Din Nasir, sang guru sekaligus sahabat yang selalu siap mendengar curahat dan keluh kesahnya; Ditemani secangkir kopi panas…
Hud-hud Musa:
Guru, hari ini aku resah. Di sebuah kafe kulihat puluhan wajah menunduk pada layar.
Ada kakek di pojok, duduk sendiri, menunggu pesan yang tak kunjung datang.
Semua mata terpaku pada notifikasi — bukan pada manusia.
Kini emoji senyum lebih cepat, video call lebih praktis.
Lalu untuk apa repot menatap wajah orang di depan kita?
Apakah kemajuan digital membuat tatapan manusia tak lagi bermakna?
Dan ada lagi yang membuatku takut:
orang kini mudah menyalin pesan, copy-paste kata tanpa rasa.
Ucapan selamat, doa, bahkan belasungkawa kini seragam —
dikirim tanpa hati, diterima tanpa makna.
Komunikasi yang dulu lahir dari rasa, kini berubah jadi rutinitas mesin.
Seakan manusia perlahan menjadi robot dengan tubuh manusia —
berbicara tanpa jiwa, bertegur sapa tanpa tatapan.
Kadang aku melihat orang ramai memberi like,
tapi di dunia nyata, tetangga lapar tak tersapa.
Ada ibu menunggu anaknya pulang, tapi sang anak sibuk dengan notifikasi.
Apakah empati kini berpindah ke layar, Guru?
Din Nasir:
Hud-hud, engkau mengingatkanku pada pertanyaan lama:
Apakah api hanya memberi terang, atau juga bisa membakar?
Teknologi pun begitu. Ia bisa jadi jembatan, tapi juga bisa menjadi dinding.
Kau bertanya: apakah tatapan masih penting?
Aku balik bertanya kepadamu:
Apakah menurutmu emoji tersenyum dapat menggantikan tatapan seorang ibu kepada anaknya?
Hud-hud Musa:
Tentu tidak, Guru. Emoji hanya tanda, bukan rasa.
Tatapan ibu punya kehangatan yang tak tergantikan.
Din Nasir:
Benar. Tatapan adalah pengakuan bahwa orang lain sungguh hadir.
Ketika tatapan hilang, martabat manusia pun perlahan memudar.
Namun tentang pesan copy-paste yang kau keluhkan itu,
aku melihatnya sebagai tanda bahwa manusia kehilangan ritme kemanusiaan.
Teknologi membuat segalanya cepat,
tapi manusia kehilangan ruang untuk berhenti sejenak —
menyapa dengan rasa, menulis dengan hati, dan berpikir sebelum mengirimkan kata.
Maka, Hud-hud, kita memerlukan sesuatu yang kita sebut sebagai “prinsip perlambatan.”
Hud-hud Musa:
Prinsip perlambatan? Apakah itu, Guru?
Din Nasir:
Prinsip perlambatan bukan berarti menolak kemajuan,
tetapi menyeimbangkan laju teknologi dengan kesadaran batin.
Artinya: berhenti sejenak, meluangkan waktu untuk menghadirkan diri dengan penuh perhatian.
Sebelum mengirim pesan, pikirkan apakah kata itu lahir dari rasa.
Sebelum menekan send, tanyakan: apakah ini akan menguatkan atau melukai?
Luangkan waktu untuk menoleh, menatap wajah orang tua, teman, atau tetangga.
Karena kadang satu tatapan tulus jauh lebih berarti daripada seribu notifikasi.
“Perlambatan” bukan kelemahan, Hud-hud.
Ia adalah bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia menegaskan bahwa komunikasi sejati memerlukan waktu, kesadaran, dan rasa.
Hud-hud Musa:
Aku mengerti sekarang, Guru.
Kecepatan membuatku merasa efisien,
tapi perlahan aku kehilangan kedalaman.
Din Nasir:
Begitulah, Nak. Dunia digital membuat kita merasa dekat, tapi diam-diam menjauhkan.
Tatapan adalah bahasa nilai yang tak bisa ditransfer lewat emoji.
Tanpa tatapan, jiwa manusia bisa kering di tengah banjir cahaya layar.
Inilah tantangan kemanusiaan, sila kedua Pancasila, di tengah arus algoritma.
Ingatlah, Hud-hud, nilai Pancasila juga lahir dari tatapan:
tatapan para pendiri bangsa yang saling percaya,
tatapan gotong royong di desa-desa,
tatapan guru yang meyakinkan muridnya bahwa ia bisa belajar.
Tatapan adalah ibadah kecil — sederhana, tapi menumbuhkan hormat dan cinta.
Hud-hud Musa:
Aku akan belajar menatap lagi, Guru.
Menyapa dengan hati, menulis dengan rasa, dan menahan diri sebelum berbicara.
Din Nasir:
Itulah awalnya, Nak.
Biarlah teknologi jadi cahaya, tapi tatapan tetap jadi hangatnya api.
Besok jika engkau tiba membawa kegelisahan yang lain,
datanglah kembali ke Balé Beléq.
Karena zaman terus bergerak, dan nilai harus terus dijaga.
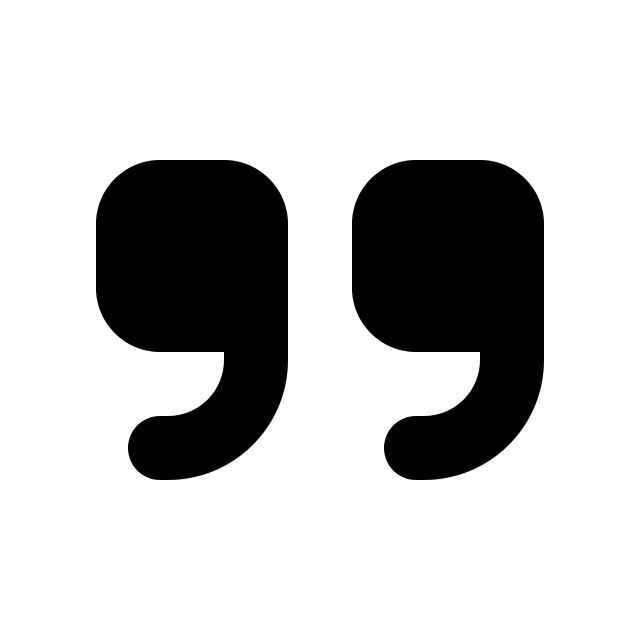
Teknologi dapat mempercepat pesan,
namun hanya empati yang mampu menyampaikan makna.
Saat komunikasi kehilangan rasa,
manusia berbicara tanpa jiwa —
seperti robot yang berkulit manusia.
Kata terus mengalir, tapi hati tak lagi hadir.
Sebab tanpa martabat kemanusiaan,
percakapan hanyalah gema kosong
di tengah derasnya laju digital.
— Din Nasir, Bayan AtepBalé
Bagaimana pengalamanmu menjaga makna empati di dunia digital?
★★★★★
Tuliskan renunganmu di ruang komentar di bawah.
Setiap catatan akan menjadi bagian dari percakapan panjang kita di Bayan AtepBale, tentang iman, ilmu, amal, kemanusiaan, dan cinta.
Dari percakapan hangat lahirlah getaran rasa. Apa yang tak mampu dijawab oleh nalar, kadang hanya bisa dinyanyikan hati — bukan lagi argumen, melainkan syair yang mengalir dari getar rasa.
👉 Baca Nazam: Suara Nilai dalam Bait AtepBal



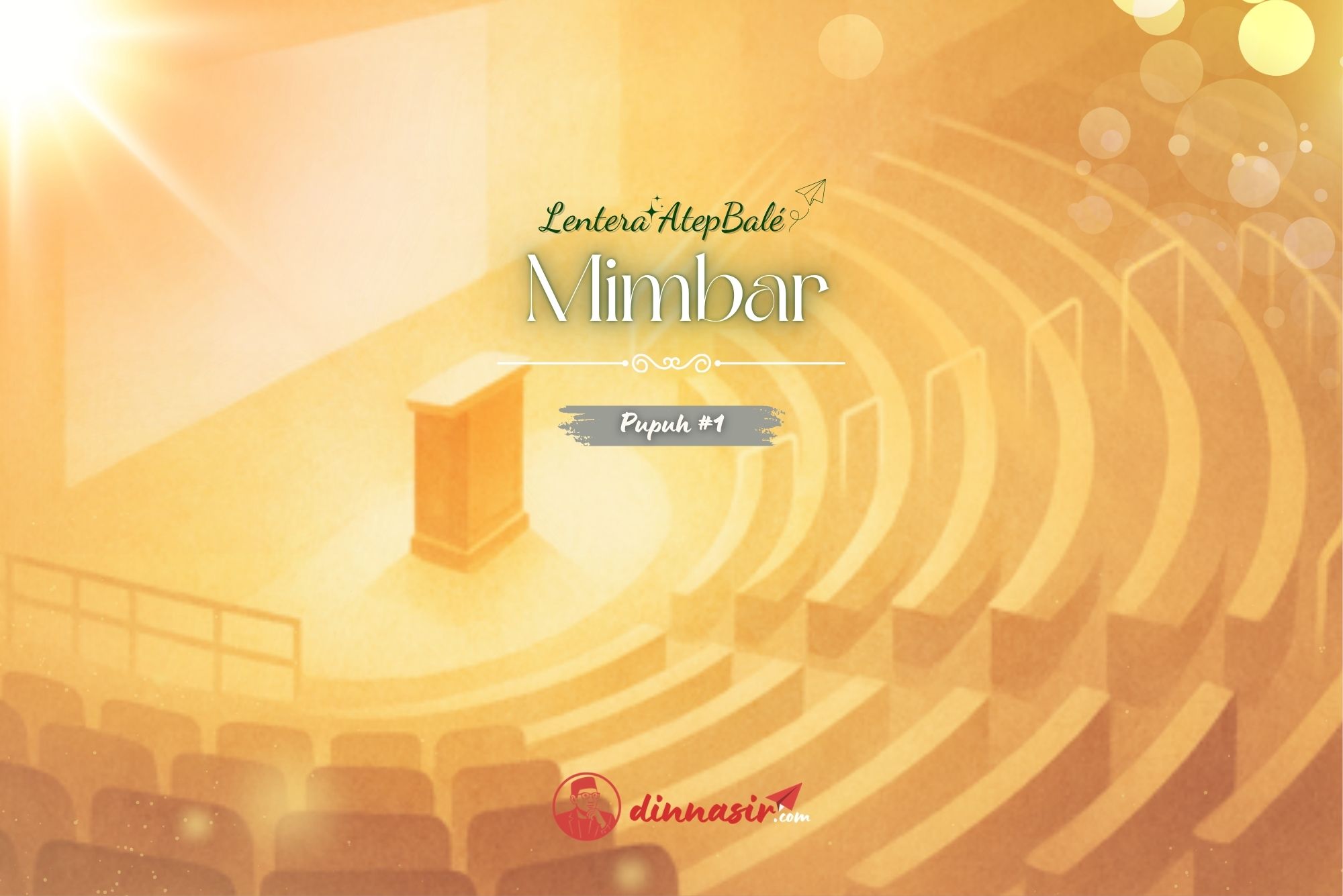






Tinggalkan Balasan